Stratifikasi sosial merupakan salah satu konsep fundamental dalam sosiologi yang membahas mengenai pengelompokan masyarakat berdasarkan kedudukan, peran, maupun akses terhadap sumber daya. Sejak zaman dahulu hingga era modern, masyarakat selalu mengenal lapisan sosial—baik yang terbentuk secara alami maupun yang dilembagakan melalui norma dan institusi sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak pernah benar-benar berada dalam kondisi egaliter sempurna, melainkan selalu dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan sosial yang nyata.
Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai pengertian stratifikasi sosial, teori-teori yang melandasinya, bentuk-bentuk stratifikasi, faktor-faktor pembentuk, hingga dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat
Pengertian Stratifikasi Sosial
Secara etimologis, stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti lapisan, dan facere yang berarti membuat. Dengan demikian, stratifikasi sosial dapat dimaknai sebagai pelapisan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan kriteria tertentu.
Menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan hierarkis. Lapisan ini ditentukan oleh status, kekayaan, kekuasaan, maupun prestise.
Dengan kata lain, stratifikasi sosial adalah sistem yang mengatur distribusi hak, kewajiban, serta kesempatan di antara anggota masyarakat, sehingga sebagian orang memiliki akses yang lebih luas dibandingkan yang lain.
Teori-teori Stratifikasi Sosial
Terdapat beberapa teori besar yang menjelaskan stratifikasi sosial, antara lain:
1. Teori Fungsionalis
Teori ini berpandangan bahwa stratifikasi sosial muncul secara alami dan diperlukan demi keteraturan masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert E. Moore, perbedaan peran dalam masyarakat menuntut adanya sistem penghargaan yang berbeda pula. Jabatan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan tanggung jawab besar biasanya diberikan status serta imbalan yang lebih tinggi.
2. Teori Konflik
Karl Marx menjelaskan stratifikasi dari sudut pandang pertentangan kelas. Menurutnya, stratifikasi lahir dari adanya kepemilikan atas alat produksi. Kaum borjuis (pemilik modal) mendominasi dan mengeksploitasi kaum proletar (pekerja), sehingga tercipta ketimpangan yang terus-menerus.
3. Teori Weberian
Max Weber mengembangkan pandangan yang lebih luas. Menurutnya, stratifikasi tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, melainkan juga dari status sosial (prestise) dan kekuasaan politik. Konsep ini dikenal dengan three-component theory yang meliputi:
-
Kelas (class) → aspek ekonomi.
-
Status (status group) → aspek sosial/kultural.
-
Partai (party) → aspek politik/kekuasaan.
Bentuk-bentuk Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, bergantung pada kriteria yang digunakan:
1. Stratifikasi Berdasarkan Kekayaan
Kekayaan menjadi indikator paling nyata dalam pelapisan masyarakat. Mereka yang memiliki aset besar, modal, atau penghasilan tinggi biasanya menempati lapisan atas. Sebaliknya, masyarakat miskin menempati lapisan bawah.
2. Stratifikasi Berdasarkan Kekuasaan
Individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan cenderung menempati posisi lebih tinggi dalam hierarki sosial. Misalnya pejabat negara, pemimpin organisasi, atau tokoh militer.
3. Stratifikasi Berdasarkan Prestise
Prestise berkaitan dengan kehormatan atau penghargaan sosial. Profesi seperti dokter, guru, atau ulama sering kali dipandang memiliki prestise tinggi meskipun tidak selalu sejalan dengan kekayaan.
4. Stratifikasi Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan berfungsi sebagai social elevator. Masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi biasanya memiliki kesempatan kerja dan status sosial yang lebih baik dibandingkan yang berpendidikan rendah.
5. Stratifikasi Tradisional
Pada masyarakat tradisional, stratifikasi sering didasarkan pada keturunan, kasta, atau adat istiadat. Misalnya sistem kasta di India atau lapisan bangsawan dalam masyarakat feodal Eropa.
Sistem Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial bisa bersifat tertutup maupun terbuka.
1. Stratifikasi Tertutup
Dalam sistem ini, peralihan status antar lapisan hampir tidak mungkin terjadi. Contoh paling jelas adalah sistem kasta di India.
2. Stratifikasi Terbuka
Dalam sistem ini, seseorang memiliki peluang untuk berpindah lapisan sosial melalui usaha, pendidikan, atau prestasi. Sistem ini umumnya berlaku di masyarakat modern yang menganut meritokrasi.
3. Stratifikasi Campuran
Merupakan kombinasi dari sistem tertutup dan terbuka. Beberapa aspek mungkin kaku (seperti keturunan bangsawan), tetapi aspek lain memungkinkan mobilitas (misalnya pendidikan atau kekayaan).
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stratifikasi Sosial
Ada beberapa faktor yang memengaruhi terbentuknya lapisan sosial, di antaranya:
-
Ekonomi – Perbedaan dalam penguasaan sumber daya ekonomi.
-
Politik – Perbedaan dalam penguasaan kekuasaan dan pengaruh.
-
Budaya – Nilai, norma, dan simbol kehormatan yang berlaku dalam masyarakat.
-
Pendidikan – Tingkat pendidikan sebagai pembeda peluang hidup.
-
Keturunan – Status keluarga yang diturunkan dari generasi sebelumnya.
Mobilitas Sosial
Stratifikasi sosial erat kaitannya dengan mobilitas sosial, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Mobilitas dapat berupa:
-
Mobilitas Vertikal Naik → ketika seseorang berhasil meningkatkan status sosialnya, misalnya anak petani menjadi pejabat.
-
Mobilitas Vertikal Turun → ketika seseorang kehilangan statusnya, misalnya pejabat yang tersangkut kasus korupsi.
-
Mobilitas Horizontal → perpindahan status tanpa mengubah lapisan sosial, misalnya seorang guru pindah dari satu sekolah ke sekolah lain.
Dampak Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial memiliki dampak positif sekaligus negatif.
Dampak Positif
-
Menciptakan Motivasi – Perbedaan status mendorong individu untuk berusaha meningkatkan kualitas diri.
-
Keteraturan Sosial – Lapisan sosial membantu pembagian peran dan fungsi dalam masyarakat.
-
Identitas Sosial – Stratifikasi memberikan rasa keanggotaan dalam kelompok tertentu.
Dampak Negatif
-
Ketidakadilan – Distribusi sumber daya yang tidak merata menimbulkan kesenjangan sosial.
-
Diskriminasi – Kelompok bawah seringkali mengalami perlakuan diskriminatif.
-
Konflik Sosial – Perbedaan kepentingan antar lapisan berpotensi menimbulkan pertentangan.
Stratifikasi Sosial dalam Konteks Modern
Di era globalisasi dan digitalisasi, stratifikasi sosial mengalami perubahan bentuk. Saat ini, selain faktor ekonomi dan politik, akses terhadap teknologi informasi juga menjadi penentu stratifikasi.
Contoh nyata: masyarakat yang melek digital cenderung memiliki akses lebih besar terhadap peluang kerja, pendidikan, dan jaringan sosial. Sebaliknya, mereka yang terpinggirkan dari teknologi berpotensi semakin tertinggal.
Selain itu, fenomena influencer atau selebriti media sosial menunjukkan bahwa prestise dan kekayaan kini bisa diperoleh melalui jalur non-tradisional, di luar sistem ekonomi formal.
Contoh Stratifikasi Sosial di Indonesia
-
Stratifikasi Ekonomi → terlihat dari perbedaan kelas antara masyarakat kaya di perkotaan dengan masyarakat miskin di pedesaan.
-
Stratifikasi Politik → tercermin dari posisi pejabat publik dibandingkan rakyat biasa.
-
Stratifikasi Kultural → tokoh agama sering kali memiliki pengaruh sosial tinggi meskipun secara ekonomi tidak dominan.
-
Stratifikasi Pendidikan → lulusan perguruan tinggi ternama memiliki kesempatan karier lebih luas dibandingkan lulusan sekolah menengah.
Upaya Mengurangi Dampak Negatif Stratifikasi
-
Pemerataan Pendidikan – Memberikan akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan.
-
Kebijakan Ekonomi Inklusif – Menciptakan lapangan kerja dan distribusi pendapatan yang lebih merata.
-
Penguatan Nilai Solidaritas – Menumbuhkan empati dan kepedulian sosial.
-
Peningkatan Literasi Digital – Agar seluruh lapisan masyarakat dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Stratifikasi sosial merupakan fenomena universal yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Ia mencerminkan perbedaan status, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya. Walaupun stratifikasi memiliki fungsi positif dalam menjaga keteraturan sosial, dampak negatifnya—seperti kesenjangan dan diskriminasi—tidak dapat diabaikan.
Di era modern, bentuk stratifikasi semakin kompleks dengan hadirnya faktor teknologi dan globalisasi. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi dalam mengurangi dampak negatif stratifikasi agar tercipta keadilan sosial.
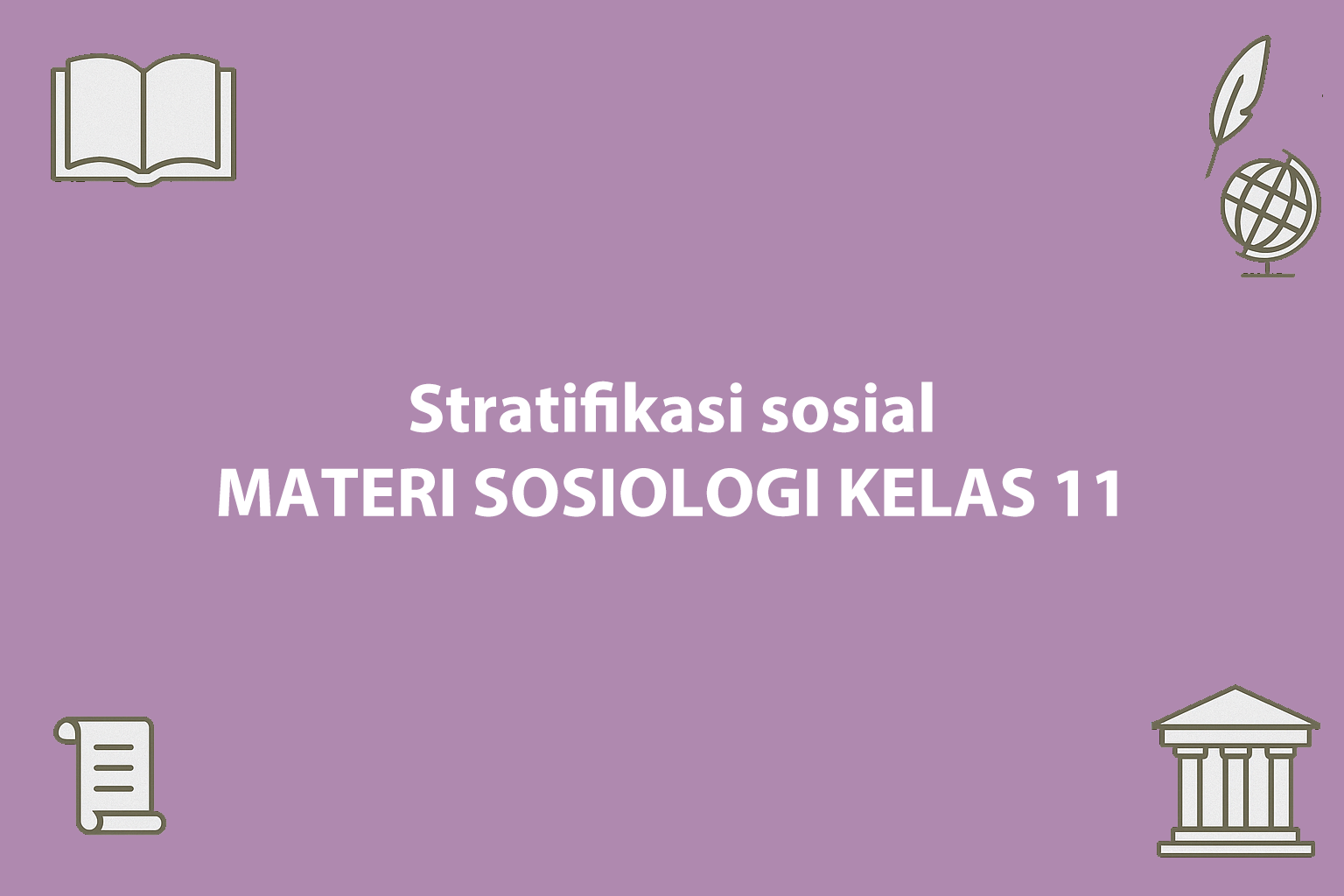
 MASUK PTN
MASUK PTN